Penulis: Abdul Hakim, Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang
Beritabanten.com – Blok apartemen di Queens jadi saksi bisu ketika seorang relawan kampanye berjalan menyusuri lorong, mengetuk setiap pintu dengan kesabaran yang hampir religius.
“Selamat pagi, saya dari kampanye Zohran Mamdani. Boleh bicara sebentar?”
Ia tidak membawa brosur penuh janji atau kamera ponsel untuk konten. Ia membawa telinga. Dan itu, di zaman ketika semua orang sibuk berbicara tapi jarang mendengar, sudah menjadi tindakan politik yang radikal.
Di balik pintu-pintu itu, warga bercerita: tentang sewa yang naik dua kali lipat, tentang bus kota yang selalu penuh, tentang anak yang terlambat sekolah karena metro mogok.
Tidak ada panggung besar, tidak ada jingle kampanye. Hanya percakapan antarmanusia: ruang yang kian langka di abad algoritma.
Kampanye semacam ini terasa nyaris aneh di Amerika Serikat yang kini hidup dalam histeria layar. Namun, bagi Zohran Mamdani, putra imigran India-Uganda, seorang Muslim, dan sosialis demokrat, politik memang bukan soal performa, melainkan pertemuan.
Ia meyakini bahwa politik yang sehat dimulai bukan dari “berapa banyak orang menonton,” melainkan “berapa banyak orang merasa didengar.”
Politik Sebagai Percakapan
Mamdani menolak gagasan bahwa politik adalah kompetisi visual antara kandidat yang memoles citra. Ia tidak meniru tradisi Amerika modern yang menjadikan politik semacam ‘Super Bowl’ ideologis: siapa yang punya iklan paling menarik, siapa yang paling sering muncul di CNN, siapa yang paling viral di TikTok.
Ia memutar balik logika itu. Ia turun ke jalan, menyeberang trotoar, mengetuk pintu, menyapa langsung para penyewa apartemen kelas pekerja.
Strategi ini bukan sekadar romantisme gerakan akar rumput (grassroots). Ini adalah pergeseran paradigma epistemik dalam cara politik dipraktikkan.
Mamdani memperlakukan warga bukan sebagai “target komunikasi,” melainkan sebagai sumber pengetahuan politik.
Dengan mendengar, ia membalik relasi kekuasaan dalam demokrasi representatif: yang diwakili memberi arah pada yang mewakili, bukan sebaliknya.
Literatur klasik mengenai partisipasi politik, dari Sidney Verba hingga Robert Putnam, sudah lama menegaskan bahwa ‘face-to-face contact’ adalah bentuk komunikasi politik yang paling efektif membangun kepercayaan.
Namun, apa yang dilakukan Mamdani lebih dari itu: ia menjadikan mendengar sebagai strategi elektoral sekaligus etika politik. Dalam dunia yang terlalu banyak bicara, mendengar adalah revolusi.
Politik dari Jalanan Queens
Latar belakang Mamdani menjelaskan banyak hal. Lahir di Kampala, Uganda, dari keluarga diaspora India, ia besar dalam kesadaran akan kolonialisme, ketimpangan, dan pencarian tempat berpijak.
Ayahnya, Mahmood Mamdani, adalah seorang pemikir besar tentang politik Afrika dan warisan kolonialisme. Ibunya, Mira Nair, sutradara film ‘Monsoon Wedding’ dan ‘The Namesake’, dikenal karena menggambarkan ketegangan antara Timur dan Barat, modernitas dan tradisi.
Dari rumah seperti itulah, Zohran tumbuh dengan kepekaan ganda: akar imigran yang tahu rasanya menjadi “yang lain”, dan pendidikan global yang membuatnya sadar bahwa sistem tidak netral.
Ia menolak jalan aman politik arus utama dan memilih Partai Sosialis Demokratik Amerika, sebuah partai yang menolak kapitalisme predator dan mendorong redistribusi kekayaan, layanan publik gratis, serta hak pekerja yang lebih kuat.
Ketika ia mencalonkan diri menjadi anggota Majelis Negara Bagian New York tahun 2020, banyak yang menganggapnya nekat. Lawannya adalah petahana kuat dari Partai Demokrat.
Namun ia menang bukan karena dana besar, melainkan karena kesetiaan pada metode lama: mengetuk pintu, berbicara, mendengar.
Lima tahun kemudian, ia mengulang sejarah: menjadi Walikota New York pertama yang beragama Islam, mengalahkan para veteran politik dengan sumber daya jauh lebih besar.
Dari Kampanye ke Kepercayaan
Mengapa strategi “kanvas pintu-ke-pintu” ini begitu efektif? Jawabannya ada pada konsep yang jarang dibicarakan dalam politik modern: kepercayaan sosial.
Kepercayaan adalah mata uang demokrasi. Ketika warga merasa tidak didengar, mereka menarik diri dari sistem, dan demokrasi pun kehilangan legitimasi.
Di banyak negara maju, partisipasi pemilih menurun tajam karena rasa muak terhadap elit politik yang dianggap terpisah dari realitas sehari-hari. Mamdani melawan tren itu dengan cara sederhana: hadir secara fisik.
Penelitian Putnam (2000) dalam, ‘Bowling Alone’, menunjukkan bahwa interaksi langsung antarmanusia memperkuat modal sosial dan kohesi komunitas. Mamdani tampaknya memahami teori ini tanpa perlu menyitasi buku: ia menghidupkannya.
Dengan memobilisasi relawan untuk berbicara dari rumah ke rumah, ia membangun jejaring sosial horizontal yang melampaui iklan digital mana pun.
Strategi ini bukan hanya taktik, melainkan kritik terhadap struktur komunikasi politik kontemporer. Dalam ekonomi atensi digital, warga direduksi menjadi algoritma: angka, klik, tayangan.
Dalam struktur semacam itu, “rakyat” bukan lagi subjek, melainkan ‘data points’ yang ditambang untuk kepentingan elektoral. Mamdani memutar balik arusnya dengan mengembalikan manusia ke pusat politik.
Namun, mari kita berhenti sejenak sebelum terlalu terpesona oleh romantika “politik yang tulus.” Di titik inilah sikap ilmiah harus bekerja.
Sebab di balik kehangatan narasi akar rumput, ada realitas keras: kampanye modern tetap memerlukan dana, organisasi, dan teknologi komunikasi.
Mengorganisir ribuan relawan, mencetak materi kampanye, menyewa ruang komunitas, menyediakan transportasi, semua itu membutuhkan logistik besar.
Bahwa Mamdani menolak iklan mahal di televisi bukan berarti ia bebas dari biaya, ia hanya mengalihkan sumber daya ke bentuk mobilisasi yang berbeda. Ia tidak menghapus struktur kapital politik; ia menafsir ulang penggunaannya.
Selain itu, ada masalah skala. Kampanye tatap muka efektif di distrik kecil seperti Queens, tetapi sulit diterapkan di negara besar dengan ratusan juta pemilih.
Model ini menuntut kepadatan sosial tinggi dan keterlibatan komunitas yang kuat, dua hal yang di banyak tempat sudah terkikis oleh urbanisasi dan individualisme digital.
Di sisi lain, kemenangan Mamdani juga tidak terlepas dari konteks politik Amerika pasca-Trump. Ketika publik jenuh dengan retorika kasar dan politik kebencian, sosok seperti Mamdani—intelektual, lembut, idealis —hadir sebagai antitesis yang menyegarkan.
Dalam politik, waktu dan konteks sering kali menentukan seefektif apa “ketulusan” bisa diterima pasar pemilih.
Politik Indonesia dan Fetisisme Viralitas
Sekarang, mari pindahkan cermin ini ke Indonesia. Di sini, politik tidak lagi dipahami sebagai ruang deliberasi, melainkan sebagai panggung pertunjukan. Calon kepala daerah kini diukur bukan dari rekam jejak, melainkan dari ‘engagement rate’.
Politisi berlomba tampil di feed media sosial, bukan di forum warga. “Dekat dengan rakyat” artinya mampir ke warung kopi sambil direkam tim konten.
Kita hidup di era politik performatif: di mana makan di warung dianggap bukti kerakyatan, meneteskan air mata dianggap empati, dan selfie dengan rakyat dianggap kerja nyata.
Dalam lanskap semacam itu, Zohran Mamdani terasa seperti anomali. Ia tidak bermain algoritma, tetapi menulis ulang naskahnya: politik sebagai percakapan, bukan sebagai konten.
Fenomena ini sering disebut sebagai fetisisme viralitas, obsesi terhadap angka impresi yang menggantikan substansi.
Ketika “viral” menjadi ukuran keberhasilan, maka yang lahir bukanlah kebijakan, melainkan citra. Bukan dialog, melainkan monolog yang dibungkus estetika ‘engagement’.
Sayangnya, banyak media kita ikut memperkuat logika ini. Alih-alih membedah gagasan atau menelusuri jejak kebijakan, media lebih suka menghitung jumlah followers atau membuat daftar “siapa yang paling disukai netizen minggu ini.”
Padahal demokrasi tidak bisa diukur dengan algoritma; ia hanya bisa dirawat dengan percakapan jujur dan ruang partisipasi nyata.
Pidato Mamdani, dengan retorika yang bernas dan argumentasi yang tajam, menjadi pengingat bahwa politik seharusnya mencerahkan, bukan menggurui.
Di Amerika, publik menyambutnya sebagai angin segar setelah bertahun-tahun terjebak dalam politik cacian era Trump. Namun, mendengarnya dari Jakarta, sulit menahan rasa getir.
Sebab di sini, pidato politik sudah lama berubah menjadi ritual yang membosankan. Para pejabat lebih senang menasihati ketimbang menjelaskan kebijakan.
Mereka berbicara seolah rakyat adalah murid yang bodoh dan harus diarahkan. Tidak ada ruang bagi tanya, apalagi debat. Demokrasi direduksi menjadi monolog moral.
Fenomena ini menjelaskan mengapa kepercayaan publik terhadap institusi politik terus menurun. Ketika pidato kehilangan isi dan hanya menyisakan gaya, warga kehilangan alasan untuk mendengarkan.
Maka, ketukan pintu yang dilakukan Mamdani terasa seperti nostalgia bagi demokrasi yang pernah kita impikan: politik yang sederhana, tulus, dan manusiawi.
Dua Dunia dan Satu Cermin
Mamdani kini berusia 34 tahun. Gibran Rakabuming, putra presiden Indonesia, berusia 38 tahun. Dua politisi muda, dua dunia yang berbeda. Yang satu membangun legitimasi dari jalanan Queens; yang lain dari ruang istana. Yang satu mengetuk pintu, yang lain mengetuk layar.
Perbandingan ini mungkin tidak adil, tapi justru karena itu menarik. Sebab ia menunjukkan perbedaan mendasar dalam ekologi politik kedua negara. Di Amerika, ada ruang bagi ‘outsider’ seperti Mamdani untuk menantang sistem.
Di Indonesia, sistem justru memastikan bahwa ‘outsider’ tidak pernah punya cukup napas untuk bertahan. Politik kita telah menjadi sistem tertutup, di mana modal finansial, koneksi keluarga, dan akses media menentukan siapa yang boleh berbicara atas nama rakyat.
Jadi, ketika publik Indonesia memuji ketulusan Mamdani, kita sebaiknya tidak berhenti di romantika.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah sistem kita masih memungkinkan model politik semacam itu tumbuh? Bisakah seorang aktivis tanpa modal besar, tanpa dinasti, tanpa patron, benar-benar mengetuk pintu rumah warga dan tetap punya peluang menang?
Jawaban yang jujur mungkin pahit. Struktur politik Indonesia, dari regulasi kampanye hingga kepemilikan media, dirancang untuk memihak mereka yang sudah punya kekuasaan.
Maka, jika politik ingin kembali menjadi percakapan yang tulus, perubahan tidak bisa hanya datang dari kandidat; ia harus datang dari reformasi sistemik: pendanaan politik transparan, media independen, dan partai yang membuka diri terhadap aspirasi akar rumput.
Kepercayaan dan Kepura-puraan
Kemenangan Mamdani memberi kita secercah harapan bahwa politik yang jujur masih mungkin ada. Namun, harapan itu rapuh.
Dalam dunia di mana citra bisa diproduksi dengan satu klik, ketulusan bisa menjadi komoditas baru. Banyak politisi belajar meniru gaya “merakyat” dengan kalkulasi yang sama dinginnya seperti strategi pemasaran.
Karena itu, ujian sejati bagi Mamdani bukanlah kemenangan, melainkan keberlanjutan. Apakah ia bisa mempertahankan politik mendengar setelah berada di kursi kekuasaan?
Apakah ia tetap mengetuk pintu ketika kamera sudah pergi? Di situlah nasib banyak reformis progresif diuji, bukan di jalan kampanye, tetapi di ruang birokrasi yang membosankan dan sarat kompromi.
Politik, seperti yang ditulis Max Weber, adalah “usaha lambat dan berat yang menuntut keberanian dan kesabaran.” Dan ketulusan, betapapun indahnya, bisa mati pelan-pelan di tangan sistem yang memuja efisiensi dan viralitas.
Politik Mengetuk Pintu, Bukan Layar
Kemenangan Zohran Mamdani adalah anomali yang menenangkan sekaligus provokasi intelektual. Ia menantang keyakinan lama bahwa politik modern harus tunduk pada logika kapital dan algoritma.
Ia menunjukkan bahwa kepercayaan, empati, dan percakapan masih bisa menjadi strategi menang.
Namun ia juga menelanjangi kelemahan demokrasi global, dunia di mana kepercayaan kini menjadi barang langka, dan bahkan “ketulusan” pun bisa dipasarkan.
Dalam konteks Indonesia, Mamdani adalah cermin. Ia memperlihatkan betapa jauhnya kita telah bergeser dari politik sebagai ruang deliberasi menuju politik sebagai tontonan.
Pertanyaan akhirnya sederhana, tapi menohok: di negeri ini, siapa yang masih mau mengetuk pintu? Siapa yang masih mau mendengar, bukan hanya berbicara?
Dan, lebih pahit lagi: apakah rakyat masih punya waktu untuk membuka pintu, ataukah kita semua sudah terlalu sibuk menatap layar? (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com

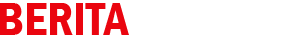


















Tinggalkan Balasan